OPINI: Saat Sumatra dan Aceh Berduka, Pemimpin Tak Boleh Berjalan Pelan
Oleh: Erni
(Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta)
BENCANA yang menimpa Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November hingga awal Desember 2025 bukan sekadar musibah tahunan, tetapi tragedi kemanusiaan berskala besar yang menyisakan luka mendalam bagi jutaan warga.
Ketika hujan ekstrem yang dipicu badai tropis mengguyur tanpa henti, banjir bandang dan longsor menghancurkan rumah, fasilitas umum, dan kehidupan masyarakat dalam hitungan jam.
Mengutip dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tanggal 11 November 2025 tencatat hampir seribu orang meninggal dunia, ratusan hilang, lebih dari lima ribu warga luka-luka, dan lebih dari satu juta jiwa kehilangan tempat tinggal.
Nilai kerusakan bahkan diperkirakan menyentuh lebih dari 60 triliun rupiah. Aceh telah menetapkan status darurat bencana sejak 28 November, dan kondisi ini terus diperpanjang seiring meluasnya dampak di berbagai kabupaten.
Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Sumatra sedang tidak baik-baik saja. Ia sedang terluka, dan luka itu membutuhkan respons yang cepat dan tepat, bukan ucapan belas kasih yang terlambat atau kebijakan yang ragu-ragu.
Namun, suara-suara dari lapangan justru banyak menggambarkan adanya kelambanan dalam respons awal pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Beberapa wilayah yang terisolasi akibat akses terputus mengaku tidak menerima bantuan dalam beberapa hari pertama.
Distribusi logistik terbatas, tenaga medis kewalahan, dan banyak warga bertahan hidup dengan persediaan seadanya. Kritik publik pun menyeruak, terutama terkait lambatnya penetapan status bencana nasional yang dianggap dapat mempercepat mobilisasi bantuan, membuka akses anggaran darurat lebih besar, serta memperkuat koordinasi lintas instansi dan antarwilayah.
Di tengah situasi darurat, setiap detik berharga dan setiap keputusan yang terlambat dapat menjadi pembeda antara hidup dan mati.
Dalam perspektif hukum Indonesia, sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk lambat mengambil peran sentral. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana secara tegas menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah penanggung jawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana bisa dikutip dari (bnpb.go.id).
UU ini bukan hanya memberikan mandat, tetapi juga memberikan wewenang untuk menetapkan kebijakan darurat, mengalokasikan anggaran khusus, dan mengambil langkah-langkah strategis demi melindungi warga negara.
Dalam pasal-pasalnya disebutkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana, memenuhi hak-hak dasar pengungsi, menyediakan sumber daya manusia dan logistik yang memadai, serta memastikan pemulihan berlangsung secepat mungkin.
Jika landasan hukum sudah jelas dan tanggung jawab negara tidak bisa ditawar, pertanyaannya kemudian adalah: mengapa respons kebencanaan masih berjalan lambat? Mengapa koordinasi masih sering tidak solid, dan informasi dari lapangan sering terlambat sampai ke pusat?
Apakah kita masih terus membiarkan masalah klasik ini terulang pada setiap bencana besar? Karena bencana bukan menunggu kesiapan pemerintah; ia datang kapan saja, bahkan ketika pemerintah sedang sibuk dengan urusan politik, birokrasi, atau wacana yang tidak menyentuh substansi penderitaan rakyat.
Dalam Islam yang menjadi nilai moral bagi mayoritas bangsa Indonesia seorang pemimpin bukan sekadar pemegang jabatan, tetapi pemikul amanah yang kelak dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di hadapan Tuhan.
Al-Qur’an dalam surah an-Nisa’ ayat 58 menegaskan pentingnya menunaikan amanah dan menetapkan keputusan dengan adil.
Prinsip amanah ini tidak bersifat simbolik, ia menuntut tindakan cepat, keputusan tepat, dan keberpihakan kepada rakyat terutama dalam kondisi darurat.
Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin dikutip dari (Hadits Shahih Al-Bukhari No. 6605 – Kitab Hukum-hukum www.hadits.id).
Amanah bukan sekadar kata, tetapi komitmen untuk hadir ketika rakyat membutuhkan, bukan hadir untuk difoto, tetapi hadir untuk bekerja.
Ketika bencana terjadi, pemimpin diuji, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan keputusan. Bencana bukan tempat bagi birokrasi panjang atau pertimbangan politik. Bencana adalah ruang di mana kemanusiaan harus menjadi prioritas tertinggi.
Pemimpin yang baik bukan mereka yang datang setelah semuanya mereda, tetapi yang pertama kali berdiri di garis depan, memastikan bantuan diterima warga, memastikan evakuasi berjalan, memastikan logistik terkirim, dan memastikan setiap korban merasa negara tidak meninggalkan mereka sendirian.
Namun, kritik publik hari-hari ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa negara kadang hadir terlalu lambat. Penolakan sementara terhadap bantuan asing, misalnya, menjadi perdebatan panjang apakah keputusan itu bijak dalam konteks darurat kemanusiaan.
Dalam kondisi korban meluas dan sumber daya terbatas, apakah lebih mulia menolak bantuan atau mengutamakan keselamatan? Nilai kemanusiaan dalam Islam jelas, menolong sesama adalah kewajiban, dan menerima pertolongan ketika kemampuan tidak mencukupi juga bagian dari kebijaksanaan.
Tidak ada kehormatan dalam membiarkan rakyat menderita hanya demi menjaga simbol kemandirian yang tidak relevan pada saat nyawa menjadi taruhannya.
Jika kita ingin keluar dari lingkaran masalah respons lambat, negeri ini perlu memperbaiki sistem kebencanaan secara menyeluruh.
Penguatan mitigasi dan sistem peringatan dini, penggunaan teknologi berbasis data real-time, koordinasi lintas lembaga yang jelas SOP-nya, hingga penguatan BPBD dan BNPB dengan tenaga profesional dan anggaran yang tidak seret birokrasi, semuanya harus menjadi prioritas.
Bencana seperti ini tidak akan menjadi yang terakhir, perubahan iklim global telah mempercepat pola ekstrem cuaca dan memperbesar risiko banjir, longsor, dan cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia.
Masalah ini bukan sekadar alam yang sedang marah, ia adalah tanda bahwa manusia dan negara harus lebih siap.
Dalam konteks Aceh dan Sumatra, masyarakat telah menunjukkan solidaritas luar biasa. Relawan datang dari berbagai daerah, donasi mengalir, dan warga saling membantu meski mereka sendiri menjadi korban.
Namun gotong royong sesama rakyat (solidaritas horizontal) ini tidak akan cukup jika tidak dibarengi kepedulian pemerintah kepada masyarakat (solidaritas vertikal), khususnya pemimpin yang memiliki kapasitas dan wewenang untuk menggerakkan sistem dalam skala besar. Rakyat sudah melakukan bagian mereka, kini negara harus melakukan bagiannya dengan lebih serius.
Pada akhirnya, bencana selalu menjadi panggilan untuk kembali kepada nilai kemanusiaan. Pemimpin yang amanah bukanlah yang hadir di akhir untuk memberi pernyataan, tetapi yang hadir sejak awal untuk memberi keputusan.
Negara yang besar bukan diukur dari gedung-gedungnya, tetapi dari bagaimana ia melindungi rakyatnya ketika keadaan paling sulit sedang terjadi.
Bencana Sumatra dan Aceh ini adalah pengingat keras bahwa kita membutuhkan pemimpin yang bergerak cepat, sistem yang tangguh, dan keberanian untuk menempatkan nyawa manusia di atas segala pertimbangan.
Solusi ke depan tidak bisa hanya ditulis atau dipidatokan. Ia harus diwujudkan. Setiap tragedi harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki diri. Setiap korban harus menjadi alasan mengapa perbaikan sistem tidak boleh menunggu.
Setiap bencana harus menjadi pintu untuk menciptakan kebijakan yang lebih manusiawi, responsif, dan berbasis nilai-nilai luhur yang kita yakini.
Jika negara ingin benar-benar hadir, maka kehadiran itu harus nyata, cepat, dan berpihak kepada yang terkena bencana.
Pemimpin harus ingat bahwa amanah bukan tanda kehormatan, tetapi kewajiban untuk bertindak. Dan bagi rakyat Sumatra dan Aceh yang sedang terluka, mereka membutuhkan negara yang tidak hanya melihat, tetapi bergerak. Tidak hanya berbicara, tetapi bekerja. Tidak hanya berjanji, tetapi membuktikan. (*)




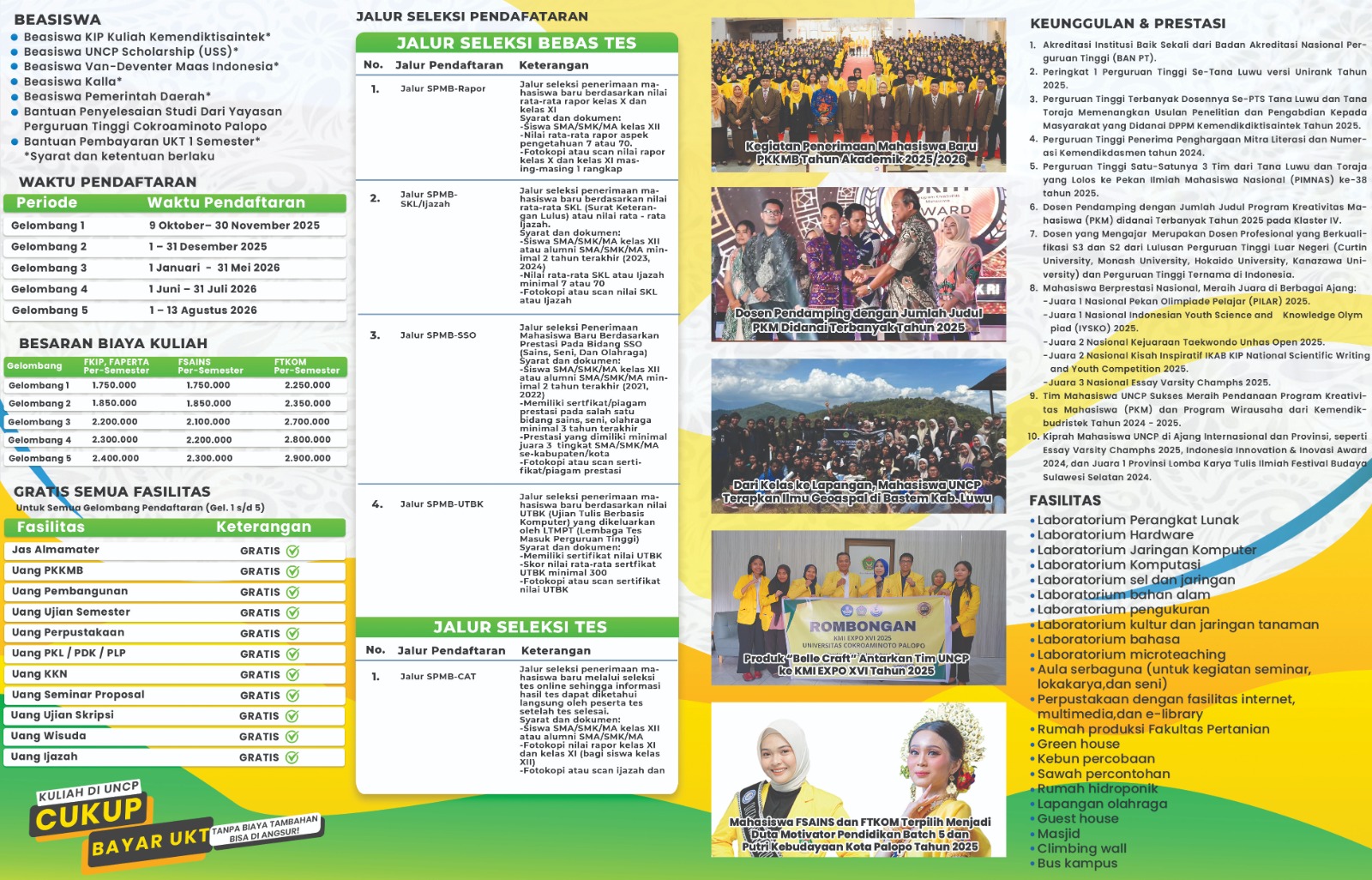













Tinggalkan Balasan