OPINI: Ancaman Pilkada 2020; Politik Siri’ Versus Politik Mate Siri’.
Oleh: Hasan Sufyan
(Ketua KPU Luwu)
SEJAK dimulai tradisi pemilihan kepala daerah langsung, hampir setiap orang setuju bahwa politik itu mahal, dan hanya orang-orang yang berduit yang bisa masuk ke gelanggang politik.
Bagi mereka yang tidak memiliki uang milyaran rupiah, masuk ke dunia politik seperti dianggap pekerjaan sia-sia, bahkan bisa tertuduh menjerumuskan dan menenggelamkan diri dalam lumpur dosa.
Mendengar argumen sinis seperti itu, membuat saya membayangkan dunia politik ibarat sindikat kejahatan tingkat tinggi, dimana semua hal dihalalkan, licik, culas, intrik, tipu menipu, semua menyatu, semua terbungkus rapi dan bersih, diluarnya hanya menampakkan kealiman dan kepedulian yang penuh kepalsuan.
Sungguh penggambaran yang sangat ngeri dan menakutkan, dan saya anggap sebagai persepsi yang brutal terhadap politik.
Sekuat apapun saya menolak persepsi yang saya anggap brutal itu, toh fakta politik yang seperti itu seringkali terlihat didepan mata.
Harga kemanusiaan terbeli dengah harga murah meriah, tidak sedikit para politisi menghabiskan uang ratusan juta sampai milyaran demi meraup suara pemilih, perdagangan dan jual beli suara menjadi aktivitas biasa yang dihalalkan. Kesimpulannya, tidak banyak duit tidak menang pilkada.
Di sisi lain, tidak sedikit saya jumpai, politisi juga mengeluh dan terbebani dengan praktek jual beli suara seperti ini, dan banyak politisi yang membangun argumennya dengan menyalahkan rakyat pemilih yang dianggap sudah terpapar penyakit mata duitan.
Sepertinya dunia politik kita sudah sedari awal terbiasa saling tuduh dan saling menyalahkan, politisi menuduh rakyat mata duitan, rakyat menuduh politisi berjubah kepalsuan.
CITRA POLITIK PARA POLITISI
Dalam dunia ekonomi pasar, produk yang di iklankan para pelaku usaha, selalu membutuhkan biaya besar, konon untuk iklan televisi durasi 30 detik biayanya sampai 50 juta rupiah untuk satu kali tayang, bahkan biayanya bisa lebih mahal jika tayang pada jam-jam tertentu.
Maka bisa dibayangkan berapa milyar dihabiskan satu produk jika iklannya tayang sepanjang waktu.
Dalam dunia politik, “citra diri” layaknya “produk”, juga di iklankan dan dipasarkan demi meraup suara pemilih.
Identitas diri politisi yang dianggap positif, dan bangunan citra tersebut dianggap bisa mempengaruhi preferensi pemilih.
Olehnya, citra tersebut akan di iklankan secara terus menerus kepada rakyat pemilih agar bisa mempengaruhi preferensi memilihnya.
Konsep abstrak yang biasanya sulit diukur oleh pemilih, akan menjadi slogan para politisi, semisal, peduli, cerdas, visioner, terhebat, terbaik, bersih, beriman, dan lain sebagainya.
Slogan tersebut adalah cara politisi meneguhkan citranya didepan pemilih agar mudah di ingat oleh rakyat pemilih dan menjadi pembeda identitas dengan lawan politiknya. Pembangunan citra diri seorang politisi, layaknya bahasa komunikasi produsen kepada konsumen, agar produknya laku terjual di pasaran.
Jika citra diri politisi disejajarkan dengan iklan sebuah produk, maka ada kemungkinan produk yang di iklankan tidak selalu sesuai dengan kenyataan sebenarnya, bisa jadi sebuah “produk gula” yang dianggap manis menyehatkan oleh produsen, sebenarnya berpotensi mendatangkan penyakit obesitas dan kematian bagi konsumen.
Begitupula citra diri para politisi yang dibungkus slogan atau tagline yang positif, juga menyimpan potensi keburukan dan kejahatan dibalik dirinya.
Maka rekam jejak politisi dan kebijakan, penting diperiksa rakyat pemilih sebelum menjatuhkan pilihan.
Politik berbiaya mahal, dengan membiayai marketing politik, juga biaya banyak dihabiskan mengongkosi tim pemenangan, termasuk biaya konsultan politik dan lembaga survey.
Namun parahnya, rekomendasi lembaga survey kepada politisi, biasa didapati, mereka justru mengajurkan kandidatnya untuk melakukan jual-beli suara.
Kalau pada akhirnya harus beli suara, kenapa politisi harus mengeluarkan biaya, hanya untuk mendengar nasehat politik sesat, dari konsultan lembaga survey yang disewanya?
Bukankah tanpa didengar dari konsultan atau lembaga survey sekalipun, toh para politisi ini sudah tahu dan terbiasa melakukan politik uang.
Apakah para politisi masih butuh diyakinkan lagi untuk melakukan politik transaksional oleh lembaga yang dibayar mahal oleh dirinya sendiri?
Sebuah ironi yang sangat paradoks, namun sering terjadi dalam pemilihan kepala daerah langsung.
Saya pernah diceritakan dari seorang tim pemenangan salah satu kepala daerah, kata dia, waktu perhelatan pilkada di kotanya, dari seratus ribu pemilih (100.000), atas saran dan rekomendasi dari konsultan politik, agar bisa memenangkan pilkada, enam puluh ribu pemilih harus dibayar sebesar Rp.300.000 ribu/orang, agar pemilih memilih kandidat calon kepala daerah.
Ini berarti kandidat harus mengeluarkan uang sebesar Rp18 Milyar untuk membeli suara pemilih , dengan hitungan sederhana 60.000 pemilih X Rp.300.000 = Rp. 18.000.000.000 (Delapan belas milyar rupiah).
Angka 18 milyar bagi kita yang tidak pernah memegang dan melihat langsung duit sebanyak itu, merupakan angka yang tidak rasional, pengeluaran duit yang tidak masuk akal, hanya untuk sebuah jabatan kepala daerah lima tahun.
Tapi ternyata setiap politisi punya hitungan dan rumus matematika tersendiri untuk setiap sen yang dikeluarkan.
Saya mendapat penjelasan rasional terkait biaya mahal yang dikeluarkan oleh kandidat kepala daerah, penjesan ini saya dapatkan dari dari mantan tim inti pemenangan pilkada, saat ini kepala daerah tersebut juga sementara menjabat.
Dia menjelaskan begini, jika setiap tahun anggaran APBD Kabupaten/Kota, belanja proyek barang jasa di sebuah daerah Kabupaten/Kota, misal sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah), maka lima persen dari dua ratus milyar adalah Rp10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah). Angka lima persen ini merupakan setoran bagian untuk kepala daerah dan kroninya.
Angka lima persen didapatkan dari setoran para pengusaha/kontraktor, baik pengusaha lokal maupun nasional, setoran untuk memuluskan mendapatkan proyek barang jasa di daerah.
Bahkan saya dapati pengakuan dari seorang pengusaha, untuk proyek fisik, setorannya bisa sampai 15 persen dari total nilai proyek, sedangkan untuk proyek jasa konsultan, setorannya bisa sampai 30 persen dari total nilai proyek.
Dengan matematika dasar yang sangat sederhana, 5 tahun X Rp10 Milyar = Rp50 Milyar, berarti selama lima tahun, uang yang bisa didapatkan oleh kepala daerah dan kroninya sebesar Rp50 Milyar.
Itu jika perhitungannya 5 persen, bagaimana jika setoran pengusaha 15-20 persen, tentu angka yang didapatkan oleh kepala daerah dan kroninya jauh lebih besar.
Maka secara kalkulasi ekonomi, pengeluaran Rp18 milyar saat pilkada oleh politisi, untuk mendapatkan return keuntungan jabatan, paling minimal Rp50 milyar, dengan begitu pengeluaran 18 milyar untuk setiap perhelatan pemilihan kepala daerah langsung, biayanya diangap masuk akal dan berani digelontorkan di ajang pilkada langsung.
Politik berbiaya tinggi dengan politik transaksionalnya, sangat bertolak belakang dengan “citra diri” para politisi, khususnya citra diri para calon kepala daerah.
Dengan fakta tersebut diatas, masih kah para politisi dan aktor politik ingin menuduh rakyat mata duitan?
POLITIK SIRI’ dan POLITIK MATE SIRI’
Dalam konteks budaya Sulawesi Selatan, harkat martabat dan kehormatan seseorang, bisa dinilai dari pertahanan siri’nya sebagai seorang manusia.
Tradisi menjunjung harkat kemanusiaan, dinilai dari sejauh mana seseorang menjaga siri‘ dirinya, keluarganya dan masyarakatnya.
Dalam konteks politik khususnya pilkada, siri’ bisa diidentifikasi dari sikap seorang politisi atau calon kepala daerah, sikap penghargaannya terhadap martabat kemanusiaan, dengan tidak membeli harkat dan martabat kemanusiaan seorang pemilih dengan nilai uang.
Di sisi lain, anomali sistem sosial masyarakat Sulawesi Selatan, juga bisa diidentifikasi dengan budaya mate siri‘, yakni seseorang yang dianggap berprilaku layaknya bangkai hidup, yang tidak menghiraukan tatanan nilai, harga diri dan martabat kemanusiaan.
Apapun yang orang lakukan pada dirinya, atau yang dirinya lakukan, tidak lagi menghiraukan siri’nya sebagai manusia, norma dan nilai masyarakat dia terabas, orang seperti ini disebut mate siri’na.
Karakter politik mate siri’na sangat gampang teridentifikasi setiap pelaksanaan pilkada langsung.
Dalam konteks pilkada langsung, politik siri‘ dan politik mate siri‘, terjadi setiap saat.
Para politisi yang mengandalkan uang dan politik transaksional merupakan karakter politik mate siri’ dan pemilih yang memilih karena uang dari politisi jenis ini, juga bisa disebut masyarakat mate siri’na.
Apakah siri’ orang Sulawesi Selatan akan digerus habis oleh model politik transaksional pada pelaksanaan pilkada langsung 2020? Atau justru kemenangan bagi kaum mate siri’ na?
Mari kita lihat proses dan hasil pemilihan kepala daerah langsung, yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. (*)
Rabu, 4 November 2020




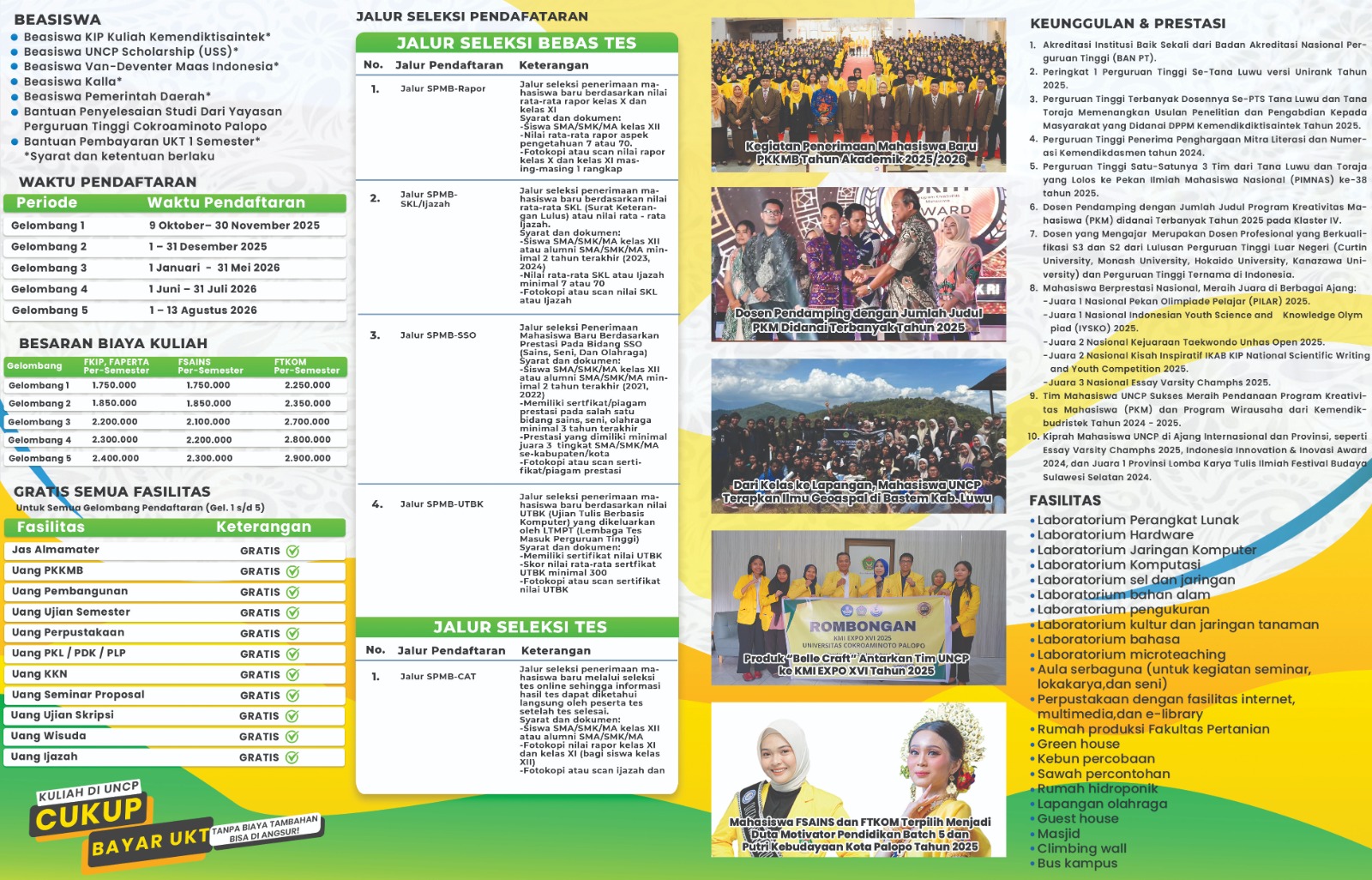













Tinggalkan Balasan