Air Mata Seorang Ayah: Perjuangan Enam Bulan Menuntut Keadilan untuk Korban yang Ditabrak Sang Dokter
DI SEBUAH rumah sederhana di Desa Gampong Jawa, Dusun Tengah, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur, seorang ayah duduk di samping putrinya yang terbaring lemah di atas ranjang.
Namanya Muhammad Nurdin, seorang pegawai rendahan di Dinas Lingkungan Hidup. Putrinya, Massyura, adalah mahasiswi yang dulunya aktif dan penuh semangat, kini hanya bisa menatap langit-langit kamar, dengan kaki yang tak lagi bisa ia gerakkan bebas seperti dulu.
Sudah enam bulan lamanya sejak kecelakaan tragis itu terjadi. Jalan nasional Medan–Banda Aceh, di Kecamatan Sungai Raya, menjadi saksi bisu ketika kendaraan roda empat yang dikendarai oleh seorang oknum dokter, dr Suci Magfira, menghantam kendaraan bermotor yang ditumpangi Massyura dari arah berlawanan.
Tubuh Massyura terpental, kakinya remuk. Empat kali operasi telah dilaluinya di RSUD dr Zubir Mahmud, rumah sakit tempat pelaku bekerja.
Namun luka yang menganga di kaki Massyura tampaknya masih kalah menyakitkan dibanding luka batin yang dirasakan keluarganya. Sebab setelah kejadian, mereka merasa ditinggalkan begitu saja—tanpa perhatian, tanpa pertanggungjawaban.
“Sampai hari ini, anak saya tidak bisa berjalan. Dokter itu—pelaku kecelakaan—datang ke rumah kami hanya sekali, itu pun setelah kami mendesak dan mendatangi Polres Kota Langsa. Saat datang, dia malah tertawa-tawa seperti tidak ada yang salah. Katanya dia justru korban,” tutur Muhammad Nurdin, menahan amarah dan sedih yang bercampur menjadi satu.
Sang ayah merasa sikap itu bukan hanya tidak etis, tapi juga menampar harga dirinya sebagai seorang ayah. Terlebih lagi, ia harus menanggung seluruh biaya pengobatan Massyura sendirian.
“Kami ini bukan orang berada. Semua biaya operasi, perawatan, bahkan kursi roda, kami tanggung sendiri,” lanjutnya.
Menurut Nurdin, kecelakaan itu jelas disebabkan oleh kelalaian. Mobil Expander yang dikendarai dr Suci melaju dari arah barat dengan kecepatan cukup tinggi.
Setelah menabrak satu pengendara motor, mobil tersebut oleng karena ban pecah, lalu banting setir ke jalur berlawanan dan menabrak sepeda motor Massyura. Dalam mobil tersebut, pelaku membawa dua anak balitanya.
Namun, yang membuat luka keluarga ini makin dalam adalah proses hukum yang berjalan lambat. Sudah enam bulan sejak kejadian 25 Oktober 2024, namun hingga kini belum ada kejelasan dari Polres Kota Langsa.
Nurdin telah berulang kali meminta kejelasan, tetapi jawaban yang diterima selalu sama: “masih dalam proses”.
“Saya hanya ingin keadilan untuk anak saya. Kalau kami tidak punya kuasa, bukan berarti kami harus diam. Anakku cacat, masa depannya hancur, masa hukum hanya jalan di tempat?” tegas Nurdin.
Massyura kini hanya bisa berbaring, menunggu waktu berjalan, sementara teman-temannya sudah kembali ke bangku kuliah.
Setiap pagi, ibunya membantu membersihkan lukanya, dan setiap malam, ayahnya menggenggam tangannya, berharap ada keajaiban. Tetapi lebih dari keajaiban, mereka menginginkan keadilan.
Kisah ini bukan hanya tentang kecelakaan. Ini tentang bagaimana sebuah keluarga kecil berjuang melawan ketidakpedulian dan ketidakadilan.
Tentang seorang ayah yang suaranya nyaris tak terdengar di tengah hiruk-pikuk sistem hukum yang lambat.
Tentang seorang anak muda yang mimpinya tertahan di antara selang infus dan nyeri tulang yang tak kunjung pulih.
Kisah ini seharusnya membuka mata kita bahwa di balik statistik kecelakaan lalu lintas, selalu ada manusia, ada kehidupan yang berubah untuk selamanya. Dan bahwa setiap korban berhak untuk didengar dan dibela, tak peduli siapa yang ada di balik kemudi.
(Iwan)




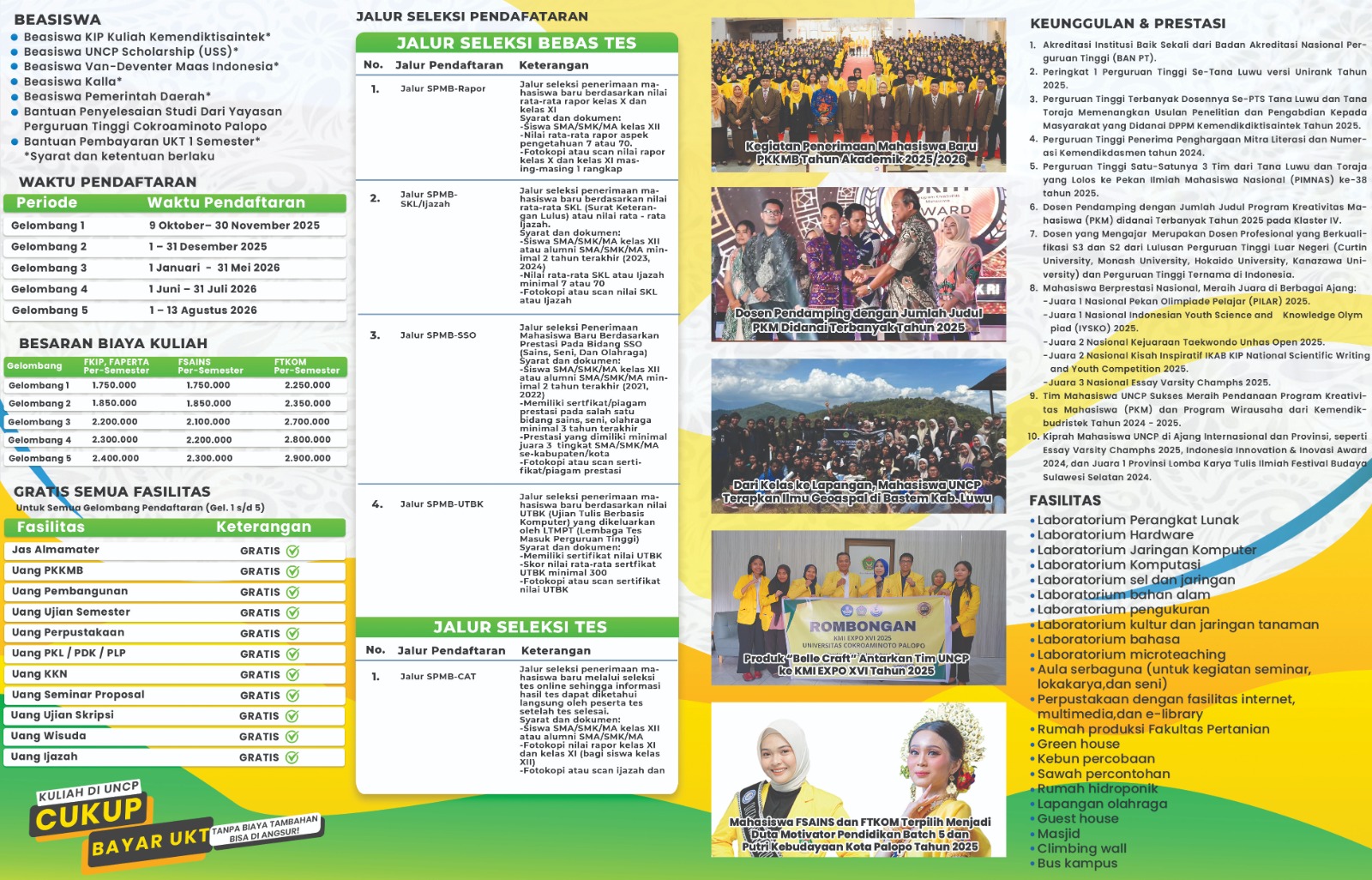













Tinggalkan Balasan