OPINI: Tritura yang Kembali Mengetuk Pintu Sejarah
Oleh : T.H. Hari Sucahyo
(Pegiat di Cross-Diciplinary Discussion Group “Sapientiae”)
TANGGAL 10 Januari selalu hadir sebagai gema, bukan sekadar angka dalam kalender sejarah Indonesia. Hari Tritura, hari ketika tiga tuntutan rakyat digemakan pada tahun 1966, menjadi simbol perlawanan sipil, kegelisahan mahasiswa, dan keberanian moral untuk menagih arah negara.
Ketika 10 Januari 2026 tiba, gema itu seakan mengetuk kembali pintu kesadaran kita, bukan untuk mengulang masa lalu secara romantik, melainkan untuk bercermin: sejauh mana republik ini belajar dari sejarahnya sendiri.
Tritura dahulu menuntut pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga. Ia lahir dari situasi politik yang buntu, ekonomi yang tercekik, dan kepercayaan publik yang retak. Enam puluh tahun berselang, wajah masalahnya berbeda, tetapi rasa sesaknya terasa familiar.
Situasi politik Indonesia hari ini bergerak dalam irama yang paradoksal. Di satu sisi, demokrasi prosedural berjalan: pemilu digelar, lembaga negara berfungsi, dan ruang digital penuh dengan percakapan politik. Di sisi lain, kelelahan publik terhadap politik kian mengental.
Koalisi gemuk membuat oposisi terasa tipis, sementara perdebatan kebijakan sering tenggelam oleh manuver kekuasaan. Demokrasi menjadi ramai tetapi tidak selalu bermakna.
Dalam suasana seperti ini, Tritura hadir bukan sebagai tuntutan literal, melainkan sebagai metafora tentang keberanian menuntut kejelasan arah, akuntabilitas, dan keberpihakan pada rakyat.
Pada tahun 1966, mahasiswa turun ke jalan dengan keyakinan bahwa negara sedang salah arah. Di awal 2026, banyak anak muda yang tidak turun ke jalan, tetapi suaranya mengalir deras di layar ponsel. Aktivisme beralih rupa: dari poster dan mimbar bebas ke utas, meme, dan video pendek.
Namun esensinya sama, kegelisahan terhadap ketimpangan, kecurigaan pada elite, dan keinginan untuk didengar. Bedanya, hari ini kebisingan informasi sering mengaburkan pesan.
Kebenaran bersaing dengan sensasi, dan kritik mudah tereduksi menjadi konten viral yang cepat dilupakan.
Tritura mengingatkan bahwa tuntutan politik memerlukan keteguhan, konsistensi, dan keberanian untuk melampaui sekadar trending topic.
Kondisi ekonomi juga menghadirkan resonansi historis. Jika Tritura dulu menuntut penurunan harga karena inflasi yang mencekik, hari ini rakyat menghadapi tekanan biaya hidup yang merangkak naik, ketidakpastian kerja di tengah disrupsi teknologi, dan jurang ketimpangan yang belum sepenuhnya tertutup.
Pertumbuhan ekonomi kerap dibanggakan, tetapi tidak selalu dirasakan merata. Pusat dan daerah, kota dan desa, pekerja formal dan informal, semuanya bergerak dalam kecepatan yang berbeda.
Dalam konteks ini, Tritura bukan tentang slogan lama, melainkan tentang tuntutan keadilan ekonomi yang relevan sepanjang zaman: harga yang masuk akal, pekerjaan yang layak, dan kebijakan yang berpihak pada yang rentan.
Politik hari ini juga ditandai oleh kuatnya personalisasi kekuasaan. Figur lebih menonjol daripada gagasan, citra lebih cepat menyebar daripada substansi.
Media sosial mempercepat proses ini, menciptakan politik yang emosional dan sering kali reaktif. Tritura mengajarkan pelajaran penting: bahwa gerakan politik yang bermakna bertumpu pada agenda, bukan sekadar tokoh.
Tiga tuntutan itu jelas, konkret, dan menyasar struktur kekuasaan. Pada 2026, tantangannya adalah merumuskan “tuntutan” yang setara, bukan untuk mengguncang negara, tetapi untuk menyehatkannya.
Reformasi birokrasi yang konsisten, penegakan hukum yang adil, dan transparansi kebijakan adalah contoh agenda yang membutuhkan tekanan publik berkelanjutan.
Dalam hubungan antara negara dan warga, ada rasa jarak yang menguat. Bahasa kebijakan sering terasa teknokratis, jauh dari pengalaman sehari-hari rakyat.
Tritura lahir dari ketidakmampuan negara kala itu menjembatani jarak tersebut. Hari ini, risiko yang sama mengintai ketika kebijakan besar diumumkan tanpa partisipasi bermakna.
Demokrasi tidak cukup dengan konsultasi formal; ia menuntut dialog yang jujur dan keterbukaan terhadap kritik. Tritura mengingatkan bahwa ketika saluran komunikasi tersumbat, jalanan atau kini, ruang publik digital akan menjadi tempat penagihan.
Namun, ada perbedaan penting yang tak boleh diabaikan. Indonesia, tahun ini bukan Indonesia tahun 1966. Institusi lebih mapan, masyarakat sipil lebih beragam, dan trauma sejarah mengajarkan kehati-hatian. Seruan perubahan hari ini harus menghindari jebakan simplifikasi dan polarisasi.
Tritura pernah menjadi pintu bagi perubahan besar yang juga menyisakan luka. Karena itu, membaca Tritura di masa kini berarti memetik keberanian moralnya tanpa mengulangi kekerasan politiknya. Ini adalah ajakan untuk perubahan yang tegas tetapi beradab, kritis tetapi konstruktif.
Peran mahasiswa dan generasi muda tetap krusial, meski bentuknya berubah. Mereka bukan hanya agen protes, tetapi juga produsen gagasan. Tantangannya adalah melampaui sinisme. Mudah untuk mengejek politik, lebih sulit untuk memperbaikinya.
Tritura menjadi pengingat bahwa idealisme memiliki harga, dan keberanian untuk membayar harga itulah yang membedakan kritik kosong dari gerakan bermakna. Saat ini, keberanian itu mungkin hadir dalam riset kebijakan, advokasi berbasis data, pengawasan anggaran, atau membangun platform partisipasi warga.
Media juga memikul tanggung jawab besar. Jika dulu pamflet dan surat kabar menjadi alat perjuangan, kini media arus utama dan platform digital menentukan arah percakapan publik. Sensasionalisme dapat merusak diskursus, sementara jurnalisme yang berintegritas dapat menjaga api akal sehat.
Tritura mengajarkan bahwa informasi adalah kekuatan; ia bisa membebaskan atau menyesatkan. Pada era algoritma, memilih untuk jujur dan mendalam adalah tindakan politik itu sendiri.
Menjelang 10 Januari 2026, pertanyaan yang patut diajukan bukanlah apakah kita membutuhkan Tritura baru, melainkan nilai apa dari Tritura yang perlu dihidupkan kembali. Keberanian menuntut akuntabilitas, kejelasan agenda, dan keberpihakan pada rakyat adalah jawabannya.
Negara tidak selalu salah, dan rakyat tidak selalu benar, tetapi dialog yang setara adalah prasyarat kemajuan. Tritura, sebagai simbol, mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa kritik akan tumpul, dan kritik tanpa tanggung jawab akan bising.
Sejarah bukan museum yang beku. Ia hidup dalam pilihan-pilihan hari ini. Apakah akan berlalu sebagai seremoni, atau menjadi momen refleksi kolektif.
Kita bisa memilih untuk sekadar mengenang, atau berani bertanya: apa tuntutan kita hari ini, kepada siapa ia ditujukan, dan bagaimana cara menagihnya tanpa merusak rumah bersama bernama Indonesia.
Jika Tritura mengetuk pintu sejarah, kitalah yang menentukan apakah pintu itu dibuka untuk angin segar perubahan, atau dibiarkan tertutup oleh rasa nyaman semu.
Tritura pernah lahir dari krisis.
Semoga refleksi Tritura tahun ini lahir dari kedewasaan. Bukan untuk mengguncang fondasi, tetapi untuk memperkuatnya. Bukan untuk mengulang luka, tetapi untuk memastikan ia tidak terulang.
Di sanalah Tritura menemukan relevansinya yang paling jujur: sebagai pengingat bahwa republik ini selalu membutuhkan warga yang berani peduli, bersuara, dan bertanggung jawab atas masa depannya sendiri. (*)




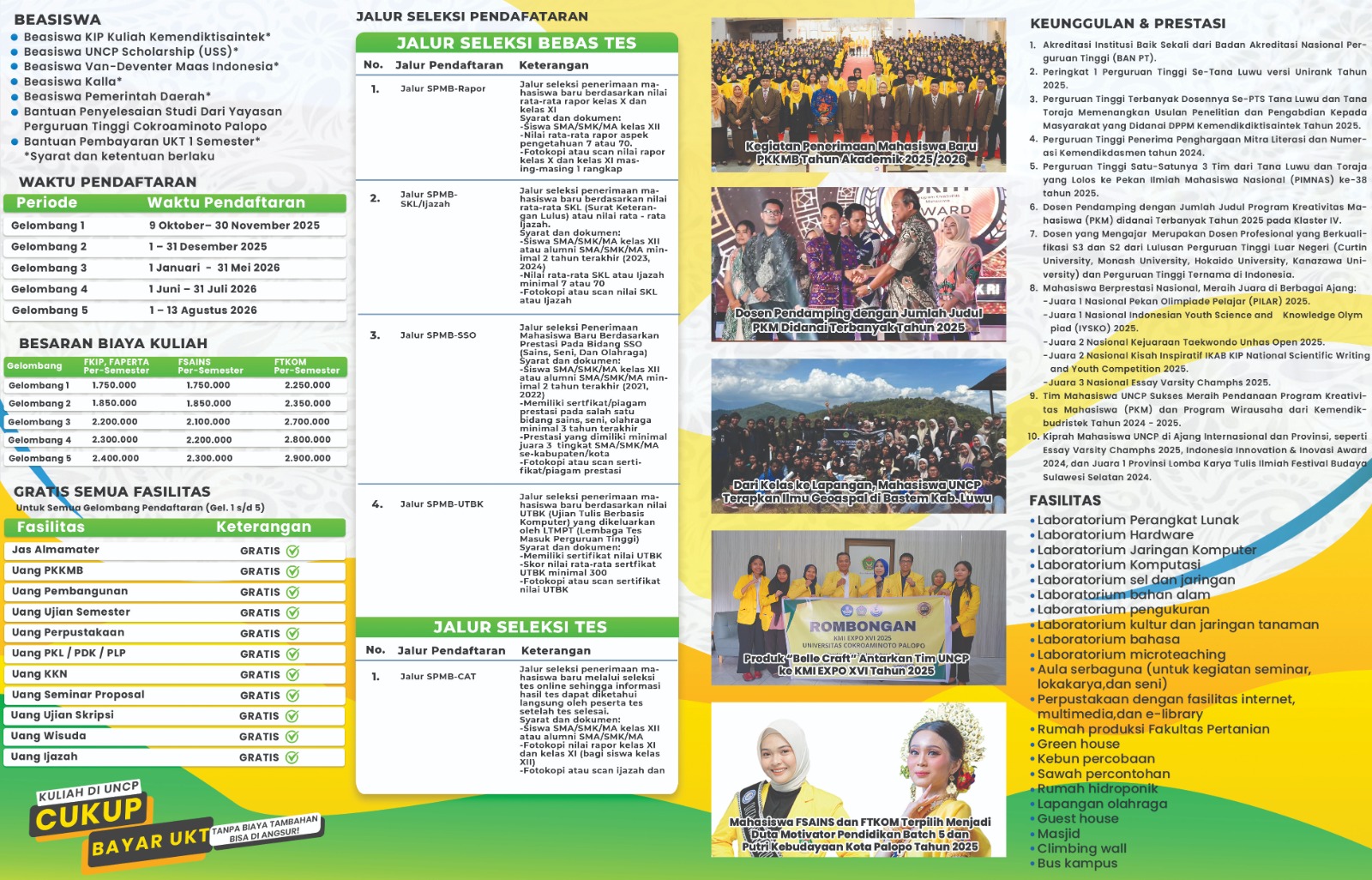













Tinggalkan Balasan